Oren dan Cikcik - Cerita Kucing
Bagian 1: Si Oren dan Kekacauan Pagi yang Biasa
Di sebuah peternakan kampung yang tidak tahu konsep sunyi, hiduplah seekor kucing jantan berbulu oranye belang-belang seperti karpet yang pernah dicuci tapi nggak dibilas. Namanya Oren. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali manggil dia begitu, tapi sejak pertama kali dia mendarat dari langit—maksudnya, dilempar anak kecil tetangga ke kandang sapi karena dikira tikus raksasa—semua langsung sepakat: ini Oren. Titik.
Peternakan tempat Oren tinggal tidak mewah. Tapi cukup ramai untuk bikin orang insomnia merasa tidak sendiri. Setiap pagi dimulai dengan trio ayam jago yang entah kenapa nggak pernah sepakat soal waktu berkokok. Si Kokok (jago tua, pensiunan adu ayam), selalu mulai jam empat subuh. Disusul si Bowo yang ngotot semua harus bangun jam lima. Dan terakhir si Kecil, jago muda labil yang baru belajar kokok tapi suaranya lebih mirip toa rusak. Biasanya dia mulai teriak pas sapi-sapi lagi pipis.
Oren tinggal di loteng kandang kambing. Tempat paling hangat, paling bau, dan paling jarang dikunjungi manusia—kombinasi yang sempurna buat kucing introvert berjiwa petualang sepertinya.
Pagi itu, Oren terbangun karena mimpi buruk: dia dikejar bebek sambil dibilang “anjing!” padahal jelas dia kucing. Begitu bangun, realitas lebih buruk. Seekor kambing jantan baru, warna abu-abu metalik (serius, bulunya kayak mobil dicat), lagi berdiri tepat di bawah loteng sambil ngemut celana dalam yang nggak tahu dapat dari mana.
Oren menguap panjang. “Miaw,” katanya pelan.
Dari bawah, kambing itu berhenti ngemut, menatap ke atas dengan tatapan waspada. Lalu: “Mbek!” dengan keras, sebelum lari seperti melihat hantu, masih sambil bawa celana dalam itu. Oren hanya mengangkat sebelah alis. Baginya, itu tadi “miaw” berarti: “Selamat pagi, makhluk bau!” Tapi tampaknya si kambing menangkapnya sebagai: “Aku kucing ninja pemburu celana. Siap melompat!”
Tak lama, dari arah belakang kandang terdengar derap langkah. Seekor bebek betina lewat dengan ekspresi seperti baru kalah debat di Twitter. Dia melihat Oren, dan langsung: “Wak wak.”
Oren merespons dengan semangat: “MIAAAW!”
Bebek itu mendadak tiarap, mengepak panik dan kabur ke arah kolam sambil teriak: “WAKWAKWAKWAK!!!” Suara seperti ketawa, tapi lebih ke trauma.
Di dunia hewan, komunikasi itu seperti main tebak kata versi hard mode. Kadang “miaw” itu artinya “halo, kamu cantik,” kadang bisa berarti “aku lapar, mana nasi gorengku?” Tapi pagi itu, Oren hanya ingin bilang, “Eh, mbak bebek, ada sarapan sisa nggak?”
Tidak ada yang paham, tentu saja. Tapi itulah hidup. Penuh kesalahpahaman, jerami, dan suara kambing kunyah plastik.
Oren pun melangkah keluar loteng, melenggang penuh gaya melewati kandang sapi, tempat dua sapi sedang saling menatap seperti pasangan LDR yang lupa tanggal jadian. Di pojok, seekor anjing kampung bernama Bodhi sedang ngiler di bawah pohon mangga, bermimpi jadi influencer hewan.
Bagian 2: Oren, Anjing Bodhi, dan Ikan Terlarang Mak Nyak
Dari semua penghuni peternakan, cuma satu makhluk yang bikin ekor Oren otomatis bergetar kayak sinyal HP di basement: Bodhi, si anjing kampung setengah malas setengah tolol.
Tapi jangan salah. Ini bukan permusuhan berdarah yang bisa masuk dokumenter hewan. Ini lebih kayak… “Aku nggak benci lo, tapi aku pengen garuk muka lo pake kaki belakang gue.” Gitu.
Bodhi sendiri sebetulnya damai. Dia punya filosofi hidup: “Kalau bukan makanan, bukan mainan, bukan tempat tidur… abaikan.” Tapi begitu Oren muncul dengan langkah angkuh dan ekspresi seperti “gue lebih tua satu jam dari lo, hormat dong”, Bodhi langsung berubah jadi mangsa yang siap diseruduk ego.
Pagi itu, Bodhi lagi tiduran santai di teras belakang dapur, tepat di bawah celah jendela tempat Mak Nyak biasa buang kulit bawang, nasi basi, dan kadang-kadang... potongan surga: ikan goreng sisa semalam.
Oren muncul dari balik tumpukan jerami dengan gaya stealth mode ala film laga. Jalan pelan. Merendah. Merunduk. Mata sipit penuh rencana jahat. Target terkunci: jendela dapur.
Dari dalam terdengar suara Mak Nyak:
> “Mak Nyak cuma masak satu ekor ini ya, yang lain jangan nyolong, awas kalo ilang!”
Dan dalam dunia hewan, kata “awas” dari manusia itu kayak... sinyal misi rahasia buat dicoba.
Oren lompat, satu kali cakar ke daun jendela—nyaris sunyi. Dia intip ke dalam. Bingo. Di atas meja, di bawah cahaya sakral matahari pagi yang menyorot lewat tirai, bersemayamlah: seekor ikan goreng lempung kesempurnaan hidup.
Cakar naik. Tangan masuk. Gigi siap.
Mak Nyak balik badan, dan... SRAT! Ikan itu menghilang dalam kedipan mata.
> “YAAMPUN! SIAPA LAGI YANG NGAMBIL INI IKAN?!”
Seketika, Oren sudah melompat turun, mulut penuh ekor ikan, lewat depan Bodhi yang refleks berdiri, panik—tapi terlalu telat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggonggong pelan (versi mental), lalu berbalik badan seolah bilang, “Gue nggak lihat apa-apa.”
Tapi Oren? Dia malah berhenti tepat di depan Bodhi, menaruh ikan sebentar, lalu “Miaw.”
Bodhi merinding. Dalam bahasa Oren, miaw barusan artinya: “Gue bisa ngambil ini. Gue bisa ambil semuanya. Bahkan hidup lo.”
Bodhi spontan duduk, menghadap ke arah lain, pura-pura jadi pot bunga.
Puas mengintimidasi dan menciptakan kekacauan tingkat dewa, Oren melenggang pergi seperti mafia habis rampok minimarket, lalu memutuskan tidur siang. Pilihan tempat? Bukan loteng, bukan atas kulkas... tapi kandang ayam.
Dan kandang ayam bukan tempat biasa. Itu wilayah negara berdaulat. Ada kode etik. Ada hierarki. Ayam-ayam betina bisa jadi manis di siang hari, tapi kalau malam? Mereka mirip geng sepeda motor dengan selimut bulu.
Tapi Oren? Mana peduli. Dia rebah di pojok kandang, tepat di atas sarang telur yang baru saja dibangun oleh Tante Ayam no.3 (yang katanya PMS hari itu).
Tiga detik. Lima detik. Ayam-ayam melongo. Satu mulai protes: “Kokokkoook!!”
Oren membuka sebelah mata. “Miaw.”
Yang artinya: “Berisik lo. Gue tidur nih.”
Dan entah kenapa... semua ayam langsung diam.
Karena di peternakan ini, ada dua hal yang tidak bisa dilawan: Mak Nyak... dan Oren.
Bagian 3: Oren, Emak Instan, dan Seekor Anak Ayam Dengan Masalah Persepsi
Oren lagi enak-enaknya tidur siang, tengkurap di sarang empuk hasil rampasan dari Tante Ayam No.3. Napasnya tenang, ngoroknya halus—kayak dengkuran meditasi. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama.
Sesuatu menggelitik di bawah perutnya.
Awalnya dia pikir itu mimpi. Mimpi digelitikin daun pisang. Atau bulu merpati. Tapi makin lama, geli itu makin intens... dan aneh.
Oren membuka satu mata. Pelan. Seperti ninja pensiunan yang mencium bahaya dari balik semak.
“Cik…?!”
Suara nyaring, kecil. Tapi mengandung urgensi.
“Cik... Cik... Cik!”
Dalam bahasa ayam:
“Emak...? Emak? Emak!!”
Oren membuka kedua mata.
Lalu...
“Miaw…”
Artinya: Apa-apaan ini, siapa yang manggil emak?
“Miaw?”
Artinya: Jangan bilang gue...
“MIAW!!!”
Artinya: APA AKU YANG DIMAKSUD, HA?!
Seekor anak ayam mungil dengan bulu kuning keemasan, masih basah setengah kering, sedang berdiri tepat di antara kaki Oren. Matanya menyala dengan harapan, seolah menemukan figur panutan, cinta sejati, dan jaminan hidup hingga dewasa.
“Cik! Cik! Cik!”
Dia terus mengekor, nabrak-nabrak perut Oren, nyungsep ke bulu dada Oren, lalu ngelendot sambil ngulet, seperti bilang: “Peluk akuuu, emak.”
Oren berdiri kaget. Loncat sejengkal. Ngibrit setengah meter.
“Miaw!! Grrr!!”
(Pergi kau binatang bayi ayam kecil yang membingungkan struktur keluarga!)
Anak ayam?
Tetap ngikutin.
“Cik! Cik! Cik!”
“Emak tungguuu~”
Oren mulai stres.
Dia goyang ekor. Diibaskan.
Anak ayam ngelipir dikit, tapi balik lagi, nabrak ekornya seperti bola karet kena angin.
Oren dorong pakai kaki depan—pelan, sopan, tapi bermakna: “Social distancing, please.”
Anak ayam?
Peluk balik kaki Oren.
Lalu Oren memutuskan satu hal: Tunjukkan siapa yang berkuasa di ekosistem!
Dia buka mulut. Lebar. Gigi kucing. Taring. Lidah menjulur. Muka kucing garang mode 100%.
Anak ayam diam sejenak.
Lalu...
masuk.
Ke mulutnya.
Bukan karena pengen dimakan, tapi kayak lagi cari tempat teduh.
Dan sesampainya di dalam...
“CEK!”
Dia mematuk lidah Oren.
Oren kesakitan campur geli. Lompat! Muter di udara!
Keluarin anak ayam pake lidah kayak lagi ludahin biji semangka.
Anak ayam jatuh... berdiri... terus lanjut:
“Cik! Cik! Cik!”
(“Mak lo marah lucu deh!”)
Dan sejak saat itu… Oren resmi dianggap ibu.
Meski dia jantan.
Meski dia kucing.
Meski dia nggak pernah daftar jadi emak.
Ke mana Oren pergi, si anak ayam ikut. Ke dapur, ikut. Ke kandang sapi, ikut. Bahkan saat Oren lagi berak di bawah pohon, si anak ayam duduk nungguin sambil nyanyi "cik cik cik" lirih, kayak fans nunggu idol k-pop keluar dari toilet.
Dan di langit yang biru, burung bangau yang melihat Oren, menghela napas, lalu bilang:
"Ya sudahlah, dia yang terpilih."
Bagian 4: Oren, Tuduhan Kekerasan, dan Hak Asasi Hewan yang Rumit
Oren mulai frustasi. Bukan frustasi yang dramatis, kayak orang ditinggal pas sayang-sayangnya. Tapi frustasi ala kucing: diam, tatapan kosong, dan buntut goyang kiri kanan kayak kipas angin rusak.
Di manapun dia pergi, “Cik! Cik! Cik!” itu nggak pernah absen.
Dia jalan, diikutin.
Dia lari, si anak ayam juga lari—walau jalannya masih kayak lego pincang.
Tidur? Diinjek.
Pup? Ditungguin, kayak ada ritual suci selesai kucing buang hajat.
Waktu Oren coba ngumpet di dapur demi mencuri ikan asin dari Mak Nyak...
Anak ayam malah muterin ikannya.
“Cik! Cik! Cik!”
(Maksudnya: “Ini ikan buat kita ya, Mak.”)
Mak Nyak:
“OYAAAAA KUCING KURANG AJAR!!”
Langsung keluar dengan sapu lidi dan teknik bela diri warisan nenek moyang.
Oren lari. Anak ayam ikut.
Mak Nyak?
Mengejar dua makhluk beda spesies yang entah kenapa bisa solid banget.
Tapi puncak neraka datang di sore yang tenang.
Anak Mak Nyak—si Iwan—bawa Whiskas, cemilan mewah yang bisa bikin Oren lupa mantan.
Oren langsung nyamperin, elegan dan sok cuek, padahal dalam hatinya konser dangdut.
Dia mencium...
Menyentuh...
Menjilat...
MULAI MENIKMATI!
Tiba-tiba...
“Cek!”
Suara batuk kecil.
Lalu...
“Cek! Cek!!”
Anak ayam, si pengikut fanatik, juga nyicipin Whiskas...
Dan KESELEK.
Muka kuningnya langsung ungu (dalam bayangan), matanya membelalak kayak tahu harga cabai naik lagi.
Oren panik.
Panik level kucing ketinggalan ikan di dapur terbuka.
Dengan insting aneh yang entah datang dari mana, Oren langsung:
– Membalik anak ayam
– Guncang kayak shaker margarita
– Ditendang pelan kayak nyalain motor jaman dulu
– Ditepuk punggungnya: Plak! Plak! Plak!
Whiskas keluar.
Anak ayam langsung napas, kayak habis bebas dari utang KPR.
Tapi...
Datanglah seekor ayam betina.
Yang ternyata aktivis HAH—Hak Asasi Hewan.
Ayam senior, bulu klimis, langkah tegas, mata seperti jaksa agung.
“Kok kamu mukulin anak, hah?!”
(Terjemahan dari “KOKOK KOKKOKK KOKOK!!!”)
Oren: “Miaw?!”
(“Lho, gue nyelametin, woy!”)
“KOKOKKOKOKOKOKOK!!!”
(Artinya: “Ini sudah pasal 3 tentang penganiayaan anak unggas. Plus pasal 7A, kekerasan dalam rumah tangga spesies campuran!”)
Oren masih kaget. Masih belum move on dari adegan muntah Whiskas.
Tapi si ayam betina makin maju.
“Kokkokkokkok!!”
(“Turunkan anak itu! Lo nggak berhak asuh! Lo bukan emak dia! Lo jantan! JANTAN!!”)
Anak ayam berdiri di samping Oren. Masih megap-megap. Tapi dengan suara serak dia bilang:
“Cik…”
(“Mak…”)
Ayam betina: freeze.
Oren: freeze.
Alam semesta: buffering.
Dan si anak ayam dengan lemah nyender ke kaki Oren, bilang pelan:
“Cik...”
(“Gue tetap pilih emak yang gebukin gue daripada emak yang datang pas udah telat.”)
Ayam betina terdiam.
Lalu pergi dengan bulu sedikit mengibas.
Tersindir. Tertohok. Terkoyak.
Oren menatap anak ayam itu.
Masih lemas. Masih nyender.
Dan untuk pertama kalinya, Oren nggak merasa risih.
Dia nggak lagi mikir: “Kenapa lo ngikutin gue?”
Tapi dia mikir:
“Gue nggak ngerti lo kenapa milih gue... tapi ya udahlah, sini, ikut lagi.”
Epilog: Oren, Cikcik, dan Takdir yang Nggak Pernah Ditulis Tuhan Tapi Keburu Viral di Langit
Akhirnya, Oren menyerah.
Bukan karena lelah. Tapi karena semesta nggak ngizinin dia bebas dari anak ayam absurd bernama Cikcik.
Mau ngumpet? Diikuti.
Mau kabur? Diikuti.
Mau tidur? Ditekan perutnya kayak bantal angin.
Mau naik ke atap? Ya, coba tebak... DIIKUTI.
Waktu itu, Oren udah naik ke titik tertinggi di dunia versi seekor kucing rumahan:
atap kandang sapi.
Duduk khidmat. Menatap langit. Mikirin hidup. Mikirin kenapa ayam bisa nyasar ke hati seekor kucing.
Cikcik pun manjat.
Langkahnya masih goyah kayak bayi ayam belajar parkour.
Dan benar saja, terpeleset.
Sayap kecilnya mengepak panik. Matanya membelalak.
Oren refleks mau nolong.
Tapi karena Tuhan sedang bikin episode sinetron yang agak sarkas,
yang jatuh malah... Oren.
Cikcik?
Selamat.
Dan menatap dari atas, kayak adegan slow motion dalam film laga.
“Cik…”
(“Sorry mak, ku gak sengaja.”)
Lain waktu, Oren lagi PDKT.
Cewek kucing anggun, bulu halus, jalan kayak model...
Oren udah keluar jurus gombal:
“Miaw...”
(“Kamu suka ikan nggak? Aku suka liat kamu.”)
Senyuman mulai muncul dari si cewek.
Lalu...
“CIK! CIK! CIK!!”
Cikcik muncul.
Dari balik semak. Dengan langkah penuh cinta dan tidak tahu waktu.
Si cewek menatap, bingung.
“Anak lo?”
Oren refleks: “Miaw?!” (“Bukan! BUKAN!!!”)
Cewek itu:
“Jadi lo cowok... bisa punya anak ayam?”
Oren panik menjelaskan. Tapi makin dijelaskan, makin absurd.
Dan akhirnya:
“Lo buaya darat ya?! Selingkuh sama ayam betina?”
Oren ditinggal.
Cikcik? Masih nyender di kaki Oren dengan tatapan bego nan bahagia.
Waktu berjalan.
Hari berganti.
Musim bergulir.
Dan... Cikcik tumbuh.
Dari anak ayam absurd jadi ayam jantan tangguh.
Bulu mengilap. Mata tajam.
Gaya jalan kayak anggota boyband yang nyasar ke arena sabung ayam.
Dan dia...
Selalu di samping Oren.
Menjaga. Melindungi. Bahkan menghadang anjing tetangga yang biasa bikin Oren kabur.
Kini, Oren jalan kayak bos.
Langkahnya santai. Kepalanya tegak.
Satu sisi Cikcik, satu sisi bayangan.
Semua penghuni peternakan mengangguk hormat.
Yang dulu menganggap Oren cuma kucing sialan, sekarang manggil:
“Oren, Precat Legendaris.”
Dia bukan preman...
Dia Precat—kucing preman berkelas.
Dengan anak ayam jadi bodyguard-nya.
Dunia mungkin bingung. Tapi Oren udah nggak peduli.
Dia tahu satu hal:
Kadang yang kita benci, bisa jadi satu-satunya yang setia sampai akhir.
Dan kalau lo tanya dia sekarang,
"Ren, lo nyesel?"
Oren bakal menjilat bulunya santai dan menjawab:
“Miaw... Gue cuma gak nyangka aja, hidup segila ini. Tapi ya, gitu deh...”
TAMAT
***
DISCLAIMER HAK CIPTA
Seluruh cerita pendek yang diposting di website www.iqbalnana.com merupakan karya orisinal yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Hak cipta sepenuhnya dimiliki oleh pemilik dan penulis situs ini.
Dilarang keras untuk:
1. Merepost (copy-paste) sebagian atau seluruh isi cerita ke platform lain tanpa izin tertulis dari pemilik situs.
2. Memperjualbelikan cerita ini dalam bentuk buku, e-book, video, audio, atau format lainnya tanpa izin resmi.
3. Menggunakan isi cerita untuk kepentingan komersial tanpa perjanjian dan persetujuan dari penulis.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Jika Anda menemukan kasus pelanggaran hak cipta terkait karya di website ini, silakan hubungi pihak pengelola situs untuk tindakan lebih lanjut.
Terima kasih telah mendukung karya orisinal dan menghormati hak cipta.
***


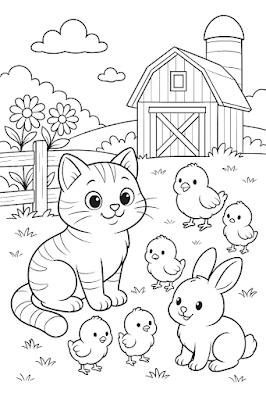



.jpeg)











.jpeg)


Posting Komentar
0 Komentar